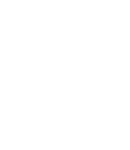Ada benarnya ujar Hasyim Wahid, adinda Gusdur, dalam salah satu sajaknya yang berjudul Monumen. Bahwa setiap monumen atau apapun karya cipta manusia yang megah nan monumental, selayaknya disikapi dengan waspada. Lantaran tak jarang dalam proses pembuatannya, monumen-monumen itu menyisakan noda merah pada lembar sejarah kemanusiaan.
Piramid Fir’aun, tampaknya disemen dengan tulang belulang rakyat Mesir. Tembok Besar China, sepertinya dicat dengan air mata rakyat Dinasti Han. Patung Liberty, juga tak kalah mengerikan. Sebab monumen negeri adidaya itu ditengarai bahan dasarnya mengenakan gincu darah Indian. Dan, Borobudur yang agung? Entah dengan dan sebanyak apa manusia Jawa membayar untuknya (Hasyim Wahid, 2005).
Fakta ini, sepertinya juga berlaku pada peristiwa proyek produksi jalan secara besar-besaran yang dikomandani oleh Mr. Herman Willem Deandels (1762-1818) –yang kelak masyhur dengan sebutan Jalan Deandels atau Jalan Raya Pos. Gubernur Jenderal yang ditugaskan di Hindia Belanda Timur atas saran Napoleon Bonaparte ini, pada saat itu, merencanakan pembangunan infrastruktur jalan antara Anyer-Panarukan yang panjangnya sekitar 1000 km. Dua titik geografis yang menyilang antara ujung barat hingga timur pulau Jawa.
Tidak cukup di situ agenda Deandels, sebab ia juga berinisiasi membangun infrastruktur lain berupa rumah sakit, tangsi-tangsi militer, pabrik senjata (di Semarang dan Surabaya), sekolah militer (di Batavia) dan benteng-benteng pertahanan (Meester Cornelis di Batavia-Jatinegara- dan Lodewijk di Surabaya). Meski demikian, tokoh yang sedikit punya kemiripan dengan Eduard Douwes Dekker (1820-1887) ini, tetap menjadikan proyek jalan sebagai prioritas utama agendanya.
Memang, motif Deandels mencetuskan proyek itu, disamping sebagai upaya memudahkan aktifitas transportasi daerah imperiumnya, juga sebagai langkah devensif dari kemungkinan terjadinya invasi Inggris yang bisa datang secara tiba-tiba. Mengingat, Jawa-lah satu-satunya jazirah imperium koalisi Belanda-Perancis yang belum jatuh ke tangan Inggris. Meski untuk hal yang kedua tidaklah terlalu berhasil, karena beberapa kali armada Inggris berhasil bertandang ke perairan laut Jawa.
Awal kali, Inggris muncul di perairan utara laut Jawa. Kedua kalinya, Inggris sekonyong memblokade Batavia dan menghancurkan labuhan kapal Belanda hingga tak berfungsi lagi. Terakhir, Inggris terlihat di Gresik di bawah komando Laksamana Pellew. Inilah, mungkin, alasan mengapa Deandels besikap sigap dengan memaksa penduduk Bumiputera untuk turut dalam barisan tentara Belanda. Tugasnya, selain untuk memperkuat benteng pertahanan, juga agar pembuatan Jalan Raya Pos cepat terealisasi. Dari titik inilah, proyek itu kerap memakan korban, terutama penduduk pribumi.
Tetapi, di balik mitos Jalan Raya Pos yang dramatik itu, ternyata masih menyisakan sejumput kontroversi yang hingga kini belum menemu titik terang. Pasalnya, pada saat itu pendokumentasian hanya dihegemoni oleh data yang dikais dari Netherland, dan mengesampingakan manuskrif lain (manuskrif laporan asli Deandels yang masih tersendat pada kekaisaran Napoleon Bonaparte, semisal) yang mungkin lebih representatif untuk mendedah ikhwal kisah ini. Silang pendapat antara jalur mana sebenarnya yang menjadi letak garapan Deandels, adalah salah satu bukti kontroversi itu. Inilah PR yang harus diselesaikan sejarawan kita!
Pertama, ini adalah pendapat yang lazim, mengutarakan bahwa Deandels memang menggurat jalan sepanjang Anyer-Panarukan. Padahal, jalan antara Anjer-Batavia saja sudah ada jauh sebelum Deandels menapakkan kakinya awalkali di Hindia Belanda (Wikipedia). Versi kedua mengatakan, sejatinya Deandels membangun jalan itu mulai dari Buitenzorg (Bogor), Cisarua, Bandung, Sumedang, Cirebon hingga sampai Pekalongan. Adapun sepanjang jalan Pekalongan-Panarukan, Deandels hanya memperlebar an sich (Het Plakaatboek van Nederlandsch Indie jilid 14). Singkatnya, menurut versi kedua, jasa Deandels hanya sebatas pada pelebaran jalan dan menjadikan trayek Surabaya-Panarukan sebagai orbit pelabuhan paling timur. Itu saja. Memang, bukan sejarah namanya jika ia tak dihiasi oleh gugusan tanda tanya!
Terlepas dari semua kontroversi itu, Deandels, sesuai dengan keyakinan umum, telah menoreh sejarah transportasi gemilang di seantero Jawa ini, yang manfaatnya dapat kita cecap hingga kini. Terutama, yang terkait dengan 1) efisiensi laju transportasi dan 2) birokrasi pengiriman (pos, semisal) yang kompatibel dan terjangkau. Tentu ini adalah pencapaian yang patut dibuat pelajaran, baik-buruknya, oleh pemerintah maupun masyarakat.
Masalahnya kini, 2 abad paska Deandels, pemerintah kita ternyata belum cukup mampu manjaga warisan maha agung dari Deandels –infrastruktur yang multimanfaat. Contoh kecil: lihatlah, untuk konteks Jatim saja, sekujur jalan maupun tata ruang kota masih banyak yang semrawut, kotor, rawan bencana alam, dan tak terawat. Tuban, misalnya. Semenanjung bibir pantai yang mengitari jalur utama (pantura)-nya dipenuhi sampah yang superjorok. Dari mulai sampah industri (limbah) hingga sampah penduduk pribumi. Semua turut berpartisipasi.
Gresik? Tak kalah semrawut. Coba tengok wilayah sekitar industri PT.Maspion dan PT.Semen Gresik, tidak ada yang tersisa selain hanya jalan sarat gompelan dan udara yang menyatu dengan polusi menyesakkan. Surabaya, apalagi! Meski Kota Pahlawan ini baru menyabet kota Adipura, tetapi yang baru dilakukan hanyalah sekadar langkah ”tambal sulam”. Artinya, tata ruang yang dipermak sebatas bagian-bagian tertentu saja. Yang dekat dengan sorotan publik dan media, tentunya. Selebihnya, mengenaskan. Got-got mampet, pengelolaan sampah yang semrawut (di TPA Benowo), maraknya pengamen liar, hingga becak yang memadati lajur kota dan menyebabkan tradisi macet, ialah pemandangan yang biasa di tubir pinggiran Surabaya.
Atau jika mau sedikit keluar dari Surabaya, niscaya akan ditemukan lebih banyak lagi wajah-wajah kota yang muram tak menyenangkan. Jalan tol Porong-Gempol (Lapindo) tentu menempati posisi pertama untuk personifikasi kota yang demikian ini. Penulis tak dapat membayangkan betapa murkanya Deandels kepada Group Bakrie jika melihat situasi yang mengangkangi teritori selatan Sidoarjo ini. Bayangkan!
Sekadar Tawaran
Tamsil di muka akan menjadi deret panjang tak berkesudahan jika terus dilanjutkan. Sebab itu, mengingat betapa urgennya infrastruktur bagi suatu negara (kota), maka pembenahan secara paripurna pun harus sesegera digalakkan. Ini memang bukan perkara mudah. Mungkin membutuhkan satu generasi untuk mewujudkannya, atau bahkan lebih. Tapi jika dimulai saat ini, kemungkinan akan lahir indikasi baik bagi generasi berikut, bisa lebih diharapkan. Karenanya, tak ada salah jika mau sedikit merenungkan tawaran ini.
Pertama. Seiring denyut desentralisasi via jargon otonomi daerahnya, Pemda mempunyai ruang cukup signifikan untuk berkreasi secara mandiri dalam membenah infrastruktur yang ada. Tentunya dengan melihat kontur masyarakat sekitar. Belum lagi, konon pada rezim SBY ini, tiga tahun terakhir, departemen PU (pekerjaan umum) mendapat kucuran dana yang tidak sedikit (2006= 31 triliun, 2007= 24 triliun, 2008= 34 triliun). Terbanyak, bahkan (Tempo, agustus 2007). Jika dapat dioptimalkan, poin ini akan menjadi dua benang perak yang dapat saling membuahkan karya positif. Dengan kata lain, proyek pembangunan infrastruktur ini sudah dapat modal utama: finansial dan konstitusional.
Kedua. Meracik infrastruktur yang ramah lingkungan. Utamanya yang berhubungan dengan drainase, sanitasi, sumber daya air, transportasi, pemukiman, serta tata ruang hijau terbuka, agar tercipta keseimbangan lingkungan. Ini penting, mengingat Indonesia (atau dunia?) kini tengah menghadapi amukan alam yang mahadahsyat. Pemanasan global dan pengelolaan sampah yang buruk adalah terdakwa yang untuk sementara dikambing-hitamkan. Banjir, longsor, gempa adalah di antara efek logis dari gejala ini. Sebab itu, reboisasi dan forestasi mutlak dibutuhkan demi kelanjutan perihidup kita di muka bumi ini. Jakarta, yang setiap lima tahun sekali kedatangan tamu banjir, mungkin bisa dibuat teladan untuk langkah antisipasi.
Ketiga. Poin ini sebagai penguat dari entri kedua. Yakni menggunakan bahan dasar yang juga ramah lingkungan. Anjuran ini berangkat dari fakta bahwa memang alam semakin ganas, maka kita sebagai penghuni harus sebisa mungkin bersahabat dengannya. Untuk konteks infrastruktur kasar, pengurangan semen mungkin bisa dibuat bahan pertimbangan. Karena, untuk satu ton semen saja, mengeluarkan satu ton karbon. Pabrik semen di dunia menyumbangkan 930 juta ton gas karbon pertahun. Wajar jika Intergovernmental Panel on Climate Change mensinyalir, bahwa semen menempati urutan kedua setelah pembangkit listrik yang menyumbangkan emisi gas rumah kaca.
Untuk contoh konkritnya, dapat ditengok terobosan F.X. Supartono yang berhasil menemu beton ramah lingkungan. Artinya, idiom ”beton terbaik menggunakan semen sebanyak-banyaknya” itu sudah punah. Sebab, saat ini semen dapat diganti dengan limbah pembakaran batubara (abu terbang) serta limbah mikrosilika. Hasilnya, tidak kalah kuat dengan semen, bahkan jauh melebihinya. Dari segi daya, beton ini mempunyai kekuatan 60 mega pascal –angka ini jauh di atas kategori beton anti gempa, 20 mega pascal. Dari segi penghematan, jelas. Bahkan ada terobosan yang sifatnya mendaur ulang (limbah).
Keempat. Mendayagunakan potensi kota yang ada. Cagar budaya, situs-situs sejarah, obyek pariwisata yang masih terisolasi, semisal. Pasalnya sejarah pembangunan infrastruktur negeri ini membuktikan, pemerintah masih enggan menghargai ikhwal yang demikian. Banyak contoh yang dapat diuraikan, tapi satu mungkin cukup mewakili: Bumi Perkemahan Panyuran, Tuban, yang kodisinya kini begitu tak tersentuh. Padahal, jika mau dilestarikan, ia akan menjadi sumber peruntungan potensial. Baik untuk Pemda maupun masyarakat setempat.
Kelima, terakhir. Infrastruktur yang berbasiskan rakyat subordinat. Ini kurang dapat perhatian dari pemerintah. Lazimnya yang pemerintah tekuni sebatas infrastruktur kaum berpunya saja, tapi lalai pada mereka yang terkucil dan minoritas. Padahal, tidak diperlukan, misalnya, dana besar untuk membangun jembatan peyeberangan. Cukup membuat setopan yang memungkinkan kaum papa, orang tua, peyandang cacat, dan anak-anak menyeberang nyaman tanpa harus mendaki jembatan penyeberangan yang tinggi demi kenyamanan para pemilik mobil. Nah!
Ala kulli hal. Semua tawaran di atas memang mudah dituliskan, tapi sulit dilaksanakan, bukan? Wallahu A’lam.